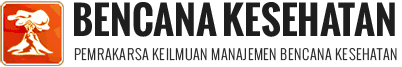Jakarta, 30 Juni 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima kunjungan edukatif dari Komunitas “Gajah Kecil,” sebuah inisiatif yang berfokus pada pengembangan dan pendidikan anak-anak. Kunjungan ini dirancang untuk memberikan pemahaman langsung mengenai meteorologi, klimatologi, geofisika, serta pentingnya kesiapsiagaan bencana kepada generasi muda.
Kegiatan diawali dengan eksplorasi Taman Alat Meteorologi, di mana anak-anak diperkenalkan pada alat-alat seperti; actinograph, evaporimeter, anemometer, dan masih banyak alat lainnya yang disambut antusias oleh anak-anak serta orang tua dengan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait alat-alat yang di tunjukkan.
Kunjungan dilanjutkan ke Museum Geofisika di Gedung A, menampilkan koleksi seismograf dari masa ke masa. Anak-anak dapat melihat langsung evolusi teknologi pendeteksi gempa, dari perangkat primitif hingga yang paling modern yang digunakan BMKG saat ini.
Momen pada sesi simulasi gempa bumi dengan kekuatan tujuh magnitudo di Gedung C disambut paling antusias. Pengalaman ini dirancang untuk mempersiapkan peserta untuk merespon gempa bumi di dunia nyata beserta tindakan yang disarankan untuk diambil saat kejadian.
Sesi materi dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Cuaca oleh Jaler Gumawang, Staf Bidang Meteorologi Publik dengan pembawaan yang interaktif untuk meningkatkan keaktifan dari para peserta. Materi mencakup klasifikasi hujan (ringan, sedang, lebat), fenomena petir, dan penjelasan visual tentang proses terjadinya hujan. Jaler juga menyoroti manfaat cuaca, aktivitas harian terkait cuaca, tindakan yang direkomendasikan sesuai kondisi cuaca, serta dampak dan penanganan cuaca ekstrem.
Tak kalah penting, Efa Endang Setiawati, Staf Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami menyampaikan materi tentang Gempa Bumi dan Tsunami. Dengan bantuan animasi, beliau menjelaskan konsep gempa bumi, tsunami perbedaan magnitudo dan intensitas, serta panduan penanganan gempa (sebelum, saat, sesudah). Penjelasan tentang penyebab tsunami dan tiga langkah tanggap tsunami pun di respon dengan aktif oleh para peserta komunitas Gajah Kecil.
Sesi ini diperkaya dengan musik interaktif BMKG “Kalau Ada Gempa”, yang disambut sangat positif oleh anak-anak. Bahkan salah satu peserta berhasil untuk mengulangi lagu dan gerakan lagu tersebut dengan akurat.
Kegiatan ditutup dengan permainan interaktif yang melatih kesiapsiagaan para peserta dengan cara mengisi tas darurat secara berpasangan dengan bahan-bahan esensial yang direkomendasikan BMKG. Permainan ini bukan hanya menghibur, tetapi juga memperkuat pemahaman praktis anak-anak tentang persiapan menghadapi situasi darurat.
Kunjungan Komunitas Gajah Kecil adalah bentuk komitmen BMKG dalam menyertakan informasi-informasi krusial terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan cara yang selalu disesuaikan untuk mudah dipahami oleh seluruh masyarakat umum.