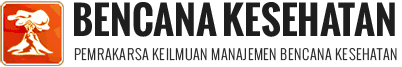Depok, Jabar (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengemukakan perubahan iklim yang kini terjadi di dunia berpotensi memicu kejadian bencana.
“Perubahan iklim terbukti meningkatkan frekuensi kejadian bencana dengan sangat drastis dan lebih ekstrem,” katanya saat Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) di Pondok Pesantren Alhamidiah, Depok, Jawa Barat, Sabtu.
Ia mengatakan tren kenaikan anomali suhu rata-rata global berbanding lurus dengan peningkatan frekuensi kejadian bencana, khususnya sejak tahun 1961.
Tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam juga dialami Indonesia dengan rata-rata kenaikan hingga 82 persen sejak 2010 hingga 2022.
"Sehingga, benar adanya bahwa peningkatan anomali suhu rata-rata baik di tingkat global maupun nasional menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi,” katanya.
Dari data yang dihimpun BNPB pada lima bulan terakhir di 2023, sudah terjadi 1.675 kejadian bencana.
“Kejadiannya didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,1 persen, dengan rincian 92,5 persen adalah bencana hidrometeorologi basah dan 6,6 persen merupakan bencana hidrometeorologi kering. Sisanya merupakan bencana geologi dan vulkanologi,” katanya.
Untuk bencana hidrometeorologi basah, akar permasalahan yang utama adalah urbanisasi yang memberikan tekanan pada lingkungan di hilir, dan alih fungsi lahan baik secara sistematis maupun ilegal, yang mengurangi kapasitas daya serap, baik karbon maupun air mulai dari hulu hingga hilir, kata Suharyanto menambahkan.
Ia mengatakan urbanisasi juga dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dalam bentuk pembuangan asap kendaraan, pabrik maupun lainnya, sehingga menjadikan kualitas udara tidak sehat.
Sedangkan alih fungsi lahan biasanya menyebabkan pengurangan vegetasi yang menyebabkan kemampuan alam dalam menyerap karbon melemah dan meningkatkan kerentanan banjir dan longsor karena air tidak terserap secara optimal.
Ia mengatakan dampak perubahan iklim tidak hanya terjadi di wilayah hulu, peningkatan suhu global memicu tren kenaikan tinggi muka laut.
“Terjadi peningkatan frekuensi kejadian banjir dari laut (rob). Diperparah oleh kerusakan ekosistem pesisir," ujarnya.
Catatan BNPB dalam tiga tahun terakhir jumlah kejadian bencana banjir rob meningkat 46 persen dari 35 kali kejadian di tahun 2020 menjadi 75 kejadian di 2022.
Selain hidrometeorologi basah, bencana hidrometeorologi kering sudah mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
“Terjadi kenaikan frekuensi kejadian kebakaran hutan dari minggu ke minggu, sehingga beberapa daerah sudah menetapkan status siaga darurat," katanya.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan luas lahan terdampak kebakaran hutan dan lahan, khususnya lahan gambut berbanding lurus dengan emisi karbon yang dilepaskan.
Pada tahun 2019 dari 1.64 juta Ha lahan terbakar melepaskan 624 juta ton emisi karbon ke udara.
“Ini semua menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana fenomena global dan regional telah nyata berdampak pada peningkatan intensitas kejadian dan dampak bencana di tingkat lokal,” katanya.
Di akhir sambutan, Suharyanto mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen pentahelix dalam penanggulangan bencana.
“Mengatasi dampak perubahan iklim harus sama-sama kita dukung, karena Pemerintah tidak akan bisa bekerja secara optimal tanpa adanya dukungan dari berbagai elemen bangsa termasuk LPBI NU sebagai komunitas penanggulangan bencana,” katanya.
Pada agenda itu turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BNPB dengan LPBI NU untuk memperkuat kerja sama yang telah berjalan dengan baik.
Hadir bersama Kepala BNPB, Plt. Sekretaris Utama BNPB, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB dan Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
Blog
BPBD Kabupaten Mojokerto Usulkan Status Tanggap Darurat Kekeringan
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Peristiwa kebakaran hutan (karhutla) hingga ancaman kekeringan memaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto mengusulkan peningkatan status tanggap darurat bencana kekeringan. Kemarin, usulan telah diluncurkan ke meja sekda hingga Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati. Usulan ini untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang agar bisa langsung tertangani.
Dalam usulan tersebut, BPBD menyertakan empat pertimbangan utama dalam meningkatkan status kewaspadaan bencana. Di antaranya instruksi Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa agar setiap daerah segera mewaspadai setiap ancaman bencana selama tahun 2023. Lalu juga prakiraan BMKG soal fenomena gelombang El Nino yang membuat musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lebih lama, terhitung mulai Mei hingga November nanti.
Kemudian adanya permintaan dropping air bersih dari tiga desa yang sumber mata airnya mulai mengalami krisis. Dan terakhir adalah munculnya sejumlah peristiwa karhutla hingga kebakaran lahan beberapa hari terakhir. ’’Mulai tadi (kemarin, Red) sudah kami naikkan usulan ke pemda untuk diteliti sebelum ditetapkan oleh ibu Bupati (Ikfina Fahmawati, Red),’’ tegas kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, Yo’ie Afrida Soesetyo Djati.
Dalam usulannya, Yo’ie turut menyertakan sejumlah langkah penanganan. Mulai dari bantuan dropping air bersih untuk warga di tiga desa di lereng Gunung Penanggungan yang terdampak parah kekeringan. Yakni Desa Kunjorowesi yang dihuni 1.635 jiwa, Desa Manduromanggunggajah sebanyak 2.142 jiwa, serta Desa Duyung di Kecamatan Trawas sebanyak 831 jiwa.
Mulai Juni nanti, BPBD bakal memberikan bantuan air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi warga setempat. Dengan asumsi setiap hari 10 truk tangki dengan ukuran 4 ribu liter per tangki. ’’Kami sertakan pula anggaran bantuan dropping air bersih kurang lebih Rp 200 juta,’’ tambahnya.
Termasuk juga menyiagakan sejumlah petugas dan potensi relawan dan partisipasi masyarakat. Mulai dari petugas pemadam kebakaran (damkar) sebanyak 6 regu atau 59 personel, ditambah relawan dari BPBD, Tahura, dan potensi masyarakat yang jumlah ratusan. Mereka diminta siap siaga dalam penanganan bencana mulai baik pemadaman kebakaran, evakuasi korban hingga bantuan droping selama musim kemarau berjalan.
’’Sudah kami instruksikan kesiapan dalam mengantisipasi potensi bencana kekeringan, termasuk melibatkan sejumlah elemen dari kelompok masyarakat,’’ pungkasnya. (far/ron)
Kearifan Lokal dan Mitigasi Bencana
Mitigasi Bencana Alam, BRIN Fokuskan Penelitian pada Konservasi Air dan Tanah
Bogor - Humas BRIN. Indonesia menjadi salah satu negara dengan risiko bencana alam tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan letak astronomis Indonesia yang beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, serta posisinya pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Pertemuan tiga lempeng ini menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi, tsunami, serta tanah longsor.
Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak bencana alam yaitu melalui mitigasi dan adaptasi. Untuk itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi (PREE) Organisasi Hayati dan Lingkungan (OR HL) memfokuskan penelitiannya pada Daerah Aliran Sungai (DAS), hidrologi, konservasi air dan tanah.
Kepala PREE, Anang Setiawan Achmadi memandang perlu kajian riset terkait kebencanaan dari hulu hingga ke hilir yang kemudian membuka peluang riset kolaboratif dengan stakeholder. Hal ini disampaikan saat membuka Jamming Session seri ke-6 yang bertemakan Berdamai Dengan Bencana, pada Kamis (25/5) secara hibrid melalui aplikasi zoom.
Tyas Mutiara Basuki, Profesor Riset PREE mengungkapkan pentingnya penginderaan jauh (remote sensing) sebagai salah satu input mendapatkan data akurat untuk diolah dalam perencanaan pengelolaan DAS.
Tyas menyebutkan data-data yang dapat dihasilkan melalui citra satelit atau Google Earth terkait pengelolaan DAS, antara lain data kemiringan lereng, data curah hujan, suhu, kelembaban dan evapotranspirasi. Lebih jauh Tyas menambahkan manfaat penginderaan jauh bagi monitoring kondisi sebuah kawasan.
"Melalui penginderaan jauh kita juga dapat memantau pemanfaatan lahan, misalnya batas pengelolaan sebuah perkebunan atau rehabilitasi area terbuka apakah lahannya sudah hijau atau masih gersang," ungkap Tyas.
Pada kesempatan yang sama Endang Savitri Peneliti Ahli Madya PREE, berhasil menyusun peta potensi bencana banjir bandang melalui pengamatan citra lansat. "Berbeda dengan bencana banjir pada umumnya, banjir bandang tidak selalu didahului dengan hujan deras. Ia bahkan dapat dipicu dengan terjadinya gempa bumi seperti kejadian banjir bandang di Luwu Utara tahun 2020," terang Endang. Ia meyakini peta kebencanaan yang dihasilkannya bersama tim berbeda dengan peta yang dikeluarkan BNPP yang lebih fokus pada daerah yang berdampak bencana.
Selain penginderaan jauh, penerapan teknologi konservasi sumberdaya tanah dan air juga memegang peranan yang tak kalah penting untuk pengendalian bencana. Peneliti Ahli Madya PREE bidang konservasi tanah dan air, Rahardyan Nugroho Adi menguraikan pentingnya monitoring tata air untuk mengetahui perkembangan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas aliran air dari suatu DAS.
Adi menegaskan teknologi pengelolaan air pada prinsipnya supaya air yang beredar sesuai siklus hidrologi jumlahnya tetap atau seimbang. "Kekurangan atau air yang berlebih dapat menyebabkan bencana alam kekeringan dan banjir," ujar Adi yang akrab disapa Didi menyimpulkan.
Ryke Nandini dan Wuri Handayani, Peneliti Ahli Madya PREE merinci teknik konservasi air dan tanah di daerah hulu dan tengah DAS. Teknik konservasi di daerah hulu terutama untuk mengatasi masalah lahan kritis, longsor lahan, dan erosi. Hal ini biasanya diatasi dengan teknik terasering, matras erosi dan pengolahan tanah.
"Kearifan lokal masyarakat di setiap daerah dalam mengelola sumberdaya tanah dan air di lahan mereka penting juga kita catat. Praktik pengelolaan lahan yang sudah puluhan tahun terbukti mempertahankan produktivitas lahan, sering kali menjadi dasar pengembangan teknologi konservasi sumberdaya tanah dan air yang kini dikembangkan para peneliti," terang Wuri menambahkan.
Purwanto, Peneliti Ahli Utama PREE bidang ekonomi sumberdaya memaparkan konsep Berdamai dengan Bencana atau adaptasi dari sudut pandang sosial. "Air dan api, kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Maka air jangan sampai menjadi air bah. Air di sekitar kita semaksimal mungkin dijaga kualitas dan seminimal mungkin dibuang ke saluran terbuka. Kewajiban setiap pengguna lahan menerapkan teknik konservasi air dan tanah di lahannya," terang Purwanto.
Ia meyakini kearifan lokal petani perlu diadopsi dan dikembangkan seperti dalam pemilihan komoditas pertanian yang tahan kering. "Sistem penanaman tumpang gilir di beberapa wilayah Nusantara serta pembuatan sumur renteng terbukti mampu meningkatkan adaptasi masyarakat lokal dengan bencana kekeringan," ungkap Purwanto.
Bincang konservasi tanah dan air untuk mitigasi dan berdamai dengan bencana dipimpin Hunggul Yudono Setio Hadinugroho, Peneliti Ahli Utama PREE sebagai moderator. "Diskusi kita hari ini dilaksanakan dengan konsep Rumah Cerdas, yaitu rumah tempat berbagi cerita seputar DAS, semoga bermanfaat bagi kita semua," pungkas Hunggul. (ugi/ed:jml)
Resiliensi Bencana Memerlukan Strategi dan Manajemen Kerja
MUHAMMADIYAH.OR.ID, KUDUS – Kerja atau aktivitas resiliensi bencana bukan kaleng-kaleng, tetapi di dalam penuh dengan kompleksitas. Maka penting untuk menyusun strategi dalam melakukan tindakan, bukan hanya datang memberi bantuan dan hilang.
Demikian rangkuman atas yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Budi Setiawan dalam Rapat Kerja Pimpinan LRB Pusat pada, Sabtu (27/5) di Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU).
“Jadi kerja kita ini harus ada kekuatan yang menekan yang harus muncul dalam semangat resiliensi itu sendiri. Ini bukan kerja biasa, dan harus tertanam dalam benak diri.” Kata Budi Setiawan.
Maka bagi setiap Relawan Muhammadiyah yang bergabung dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), maka secara otomatis harusnya menyadari bahwa kerja-kerja pertolongan yang dia berikan bukan suatu yang kaleng-kaleng.
Sebagai relawan yang bergabung dalam sebuah sistem organisasi, imbuh Budi, dalam menghadapi persoalan atau masalah tidak digantung dan selesai dengan sendirinya, melainkan harus memiliki target waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Target penyelesaian persoalan atau masalah tersebut akan berimplikasi pada persoalan atau masalah selanjutnya. Budi mengibaratkan, seperti menaiki sebuah kapal yang berlayar, pantang pulang meski badai menghadang, perjalanan harus sampai di daratan tujuan.
Dalam menghadapi persoalan konflik, Relawan Muhammadiyah tidak boleh mengambil keuntungan. Melainkan harus hadir sebagai pembangun perdamaian dan penengah konflik, serta menyediakan layanan kesehatan dan psiko-sosial.
“Respon terhadap bencana alam dan konflik merupakan tindakan kemanusiaan universal, sehingga menjalankannya untuk korban siapa saja tanpa melihat latar belakangnya.” Tutur Budi.
Budi menegaskan, dalam melakukan pertolongan terhadap siapapun, MDMC PP Muhammadiyah menggunakan berbagai strategi dengan prinsip utama adalah tetap Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).
Dalam periode lima tahun ke depan (2022-2027), MDMC mencanangkan diri sebagai Resiliensi Berkemajuan, sebagai konsekuensi bagian dari Amanat Muktamar ke-48 Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Berkemajuan.
More Articles ...
- Pemkot Padang uji coba 12 sirene tsunami, tingkatkan kesiagaan bencana
- Gelar Diskusi, BPSDM Sulteng Kembangkan Kompetensi Kepemimpinan Krisis Hadapi Resiko Bencana
- Kepala BPBD Malut Tekankan Pentingnya SPM di Bidang Penanggulangan Bencana
- Tingkatkan Operasi Penanggulangan Bencana, TNI Gelar Latihan Bersama Tentara Australia dan AS