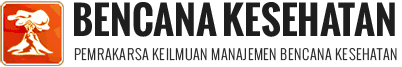Pengantar website bencana kesehatan minggu lalu membahas tentang peta respon, minggu ini akan membahas tentang klaster kesehatan. Kedua hal tersebut saling berkaitan, pasalnya peta respon wajib ada dalam klaster kesehatan. Wilayah Indonesia yang rentan bencana dan meningkatnya kejadian bencana selama satu tahun terakhir ini, memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam koordinasi penanganan bencana pada fase tanggap darurat. Salah satu strategi untuk kecepatan dan ketepatan koordinasi tersebut adalah dengan membentuk klaster kesehatan pada fase tanggap darurat bencana. Fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya belum mengetahui sistem klaster kesehatan ketika terjadi bencana. Klaster kesehatan seyogyanya dibentuk dan dikoordinir oleh dinas kesehatan. Pengalaman dari kejadian bencana di Palu, kepala Dinkes Provinsi Palu menyatakan bahwa pembentukan klaster kesehatan menolong mereka dalam membangun koordinasi dengan tim relawan yang datang. Mereka dibantu oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan relawan manajemen bencana dari akademisi untuk menjalankan sistem klaster kesehatan tersebut. Sementara sebelum terjadi bencana mereka belum mengetahui tentang klaster kesehatan. Hal yang sama juga terjadi pada bencana tsunami di Selat Sunda provinsi Lampung.
Dalam sistem klaster kesehatan akan terbangun koordinasi, kolaborasi kapasitas dan integrasi sistem antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Aktivasi klaster kesehatan terbagi menjadi 6 sub klaster yaitu (1) sub klaster pelayanan kesehatan; (2) sub klaster pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan penyiapan air bersih; (3) sub klaster kesehatan reproduksi; (4) sub klaster kesehatan jiwa; (5) sub klaster disaster victim identification /DVI ; dan (6) sub klaster gizi. Buku panduan terkait mekanisme klaster kesehatan ini masih sulit ditemukan di Indonesia. Sistem klaster kesehatan umumnya dikenalkan oleh pusat krisis kesehatan kemenkes, WHO, pokja bencana universitas dan NGO/LSM kebencanaan dalam pelatihan - pelatihan terkait penanggulangan bencana pada sektor kesehatan. Namun terdapat Undang Undang kebencanaan yang menjadi dasar yang kuat untuk pengaktifan sistem klaster. Misalnya dalam UU 36 Tahun 2009 pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) telah menyusun modul sistem koordinasi klaster dalam level internasional. Modul tersebut menjelaskan diantaranya tentang klaster dan sistem koordinasi, aktivasi klaster, fungsi dan peran klaster, pengaturan manajemen klaster, monitoring klaster dan sebagainya. Pada fase tanggap darurat ketika kapasitas koordinasi pemerintah terbatas dan mengalami kekacauan, maka pengaktifan klaster sangat diperlukan. Selanjutnya ketika sudah memasuki fase pemulihan atau recovery , klaster tidak diaktifkan dan sistem pelayanan dikembalikan seperti semula sebelum terjadi bencana.
Selengkapnya Klik Disini