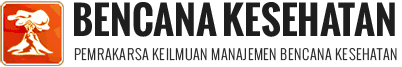Makalah ini mengkaji bagaimana wacana dan praktik desain dapat diterapkan untuk mengurangi dampak merusak dari bencana alam (tidak) dan memandu pemulihan pasca bencana yang tangguh. Terintegrasi dengan analisis sistem, desain dapat memberikan jendela inovatif untuk memahami kompleksitas pengurangan dan pemulihan risiko bencana, serta jembatan konseptual untuk cara baru membangun ketahanan sosial-ekonomi dan fisik di masyarakat yang terkena dampak bencana. Namun, keterampilan pemikir sistem dan desain utama, seperti arsitek, perencana kota, dan arsitek lanskap, jarang digunakan, meskipun kapasitas mereka ditujukkan untuk bekerja dengan masyarakat yang rentan atau terkena dampak bencana untuk mengembangkan respons spasial terpadu untuk memandu pengurangan risiko bencana dan pembangunan kembali jangka panjang setelah bencana. Makalah ini membahas kelalaian dalam manajemen bencana dan pendidikan desain melalui tinjauan penelitian tentang kontribusi desain untuk masalah bencana dan memberikan studi kasus kurikulum dan pendekatan pedagogis yang tepat untuk membangun kapasitas untuk meningkatkan kontribusi ini. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal MDPI
Makalah ini mengkaji bagaimana wacana dan praktik desain dapat diterapkan untuk mengurangi dampak merusak dari bencana alam (tidak) dan memandu pemulihan pasca bencana yang tangguh. Terintegrasi dengan analisis sistem, desain dapat memberikan jendela inovatif untuk memahami kompleksitas pengurangan dan pemulihan risiko bencana, serta jembatan konseptual untuk cara baru membangun ketahanan sosial-ekonomi dan fisik di masyarakat yang terkena dampak bencana. Namun, keterampilan pemikir sistem dan desain utama, seperti arsitek, perencana kota, dan arsitek lanskap, jarang digunakan, meskipun kapasitas mereka ditujukkan untuk bekerja dengan masyarakat yang rentan atau terkena dampak bencana untuk mengembangkan respons spasial terpadu untuk memandu pengurangan risiko bencana dan pembangunan kembali jangka panjang setelah bencana. Makalah ini membahas kelalaian dalam manajemen bencana dan pendidikan desain melalui tinjauan penelitian tentang kontribusi desain untuk masalah bencana dan memberikan studi kasus kurikulum dan pendekatan pedagogis yang tepat untuk membangun kapasitas untuk meningkatkan kontribusi ini. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal MDPI
Blog
Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan 2023
 Pengantar website minggu ini membagikan buku Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Buku ini berisi bagaimana konsep dan aktivasi klaster kesehatan dan Health Emergency Operation Center (HEOC), tenaga cadangan, logistik kesehatan, standar pelayanan minimal klaster kesehatan, kaji kebutuhan pasca bencana, sistem informasi, antisipasi insiden korban massal, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep pengelolaan krisis kesehatan melalui tiga tahapan saat pra krisis kesehatan, saat darurat kesehatan dan pasca krisis kesehatan dimana menitikberatkan kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan. Konsep tenaga cadangan sudah diregistrasi berbasis aplikasi website dan melalui tahap kredensialing, kemudian diberikan pembinaan tenaga cadangan. Ketika terjadi darurat krisis kesehatan, tenaga cadangan akan mendapatkan notifikasi dan penetapan mobilisasi di daerah terdampak. Pengelolaan logistik saat krisis kesehatan diperlukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dimulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan,pengendalian, pencatatan dan pelaporan sampai dengan penghapusan. Standar Pelayanan Minimal Klaster Kesehatan membahas jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap penduduk secara minimal dalam kondisi darurat kesehatan.
Pengantar website minggu ini membagikan buku Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kesehatan 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Buku ini berisi bagaimana konsep dan aktivasi klaster kesehatan dan Health Emergency Operation Center (HEOC), tenaga cadangan, logistik kesehatan, standar pelayanan minimal klaster kesehatan, kaji kebutuhan pasca bencana, sistem informasi, antisipasi insiden korban massal, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep pengelolaan krisis kesehatan melalui tiga tahapan saat pra krisis kesehatan, saat darurat kesehatan dan pasca krisis kesehatan dimana menitikberatkan kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan. Konsep tenaga cadangan sudah diregistrasi berbasis aplikasi website dan melalui tahap kredensialing, kemudian diberikan pembinaan tenaga cadangan. Ketika terjadi darurat krisis kesehatan, tenaga cadangan akan mendapatkan notifikasi dan penetapan mobilisasi di daerah terdampak. Pengelolaan logistik saat krisis kesehatan diperlukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif dimulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan,pengendalian, pencatatan dan pelaporan sampai dengan penghapusan. Standar Pelayanan Minimal Klaster Kesehatan membahas jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap penduduk secara minimal dalam kondisi darurat kesehatan.
Triase Saat Bencana
 Triase dilaksanakan untuk mengetahui pasien yang menjadi prioritas utama untuk cepat ditangani, memilah pasien berdasarkan kondisi kegawatan pasien (gawat darurat, gawat, tidak gawat dan meninggal). Triase dilakukan ketika menghadapi korban massal pasien dimana dalam kondisi bencana dikenal dengan "triase bencana". Keputusan untuk menerapkan triase bencana melibatkan komponen tambahan alokasi sumber daya, karena dengan kondisi bencana kemungkinan besar kebutuhan untuk melakukan triase lebih besar daripada kapasitas sumber daya yang ada. Membuat transisi ke triase bencana, mengalihkan fokus ke populasi terdampak dan menerapkan proses alokasi sumber daya memerlukan persetujuan dan tata kelola yang tepat. Terlepas dari jenis bencananya, triase harus menangani semua sumber permintaan untuk perawatan kritis, tidak hanya permintaan yang terkait dengan peristiwa lonjakan itu sendiri. Misalnya, setelah bencana alam atau serangan terorisme yang menyebabkan masuknya pasien trauma, sistem triase juga harus mampu mengalokasikan sumber daya perawatan kritis secara adil kepada pasien dengan kondisi medis yang tidak terkait dengan insiden tersebut, seperti gagal napas akibat sindrom gangguan pernapasan akut karena sepsis atau wanita dengan perdarahan pasca persalinan. Ada beberapa pertimbangan utama saat merencanakan dan memberikan triase. Pertimbangan ini termasuk keputusan penting tentang siapa yang harus dipilih untuk melakukan triase, apakah triase harus dilakukan oleh individu atau tim, apakah mereka harus mengikuti protokol atau bertindak berdasarkan intuisi klinis mereka, dan terakhir, jika menggunakan protokol, berdasarkan apa protokol tersebut. Artikel berikut membahas apa itu triase saat bencana, siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya dan kapan harus dilakukan triase. Klasifikasi triase yang paling umum didasarkan pada lokasi dan tingkat perawatan dimana triase dilakukan. Triase primer terjadi di lapangan dengan tujuan menentukan prioritas penanganan di tempat kejadian dan transportasi pasien ke rumah sakit. Tujuan dari triase sekunder bervariasi tergantung pada sifat insiden tersebut. Triase tersier terjadi di dalam rumah sakit dengan tujuan memprioritaskan pasien, dan jika diperlukan mengalokasikan sumber daya, untuk perawatan definitif (operasi atau prosedur radiologi intervensi) dan perawatan intensif (terapi penunjang kehidupan).
Triase dilaksanakan untuk mengetahui pasien yang menjadi prioritas utama untuk cepat ditangani, memilah pasien berdasarkan kondisi kegawatan pasien (gawat darurat, gawat, tidak gawat dan meninggal). Triase dilakukan ketika menghadapi korban massal pasien dimana dalam kondisi bencana dikenal dengan "triase bencana". Keputusan untuk menerapkan triase bencana melibatkan komponen tambahan alokasi sumber daya, karena dengan kondisi bencana kemungkinan besar kebutuhan untuk melakukan triase lebih besar daripada kapasitas sumber daya yang ada. Membuat transisi ke triase bencana, mengalihkan fokus ke populasi terdampak dan menerapkan proses alokasi sumber daya memerlukan persetujuan dan tata kelola yang tepat. Terlepas dari jenis bencananya, triase harus menangani semua sumber permintaan untuk perawatan kritis, tidak hanya permintaan yang terkait dengan peristiwa lonjakan itu sendiri. Misalnya, setelah bencana alam atau serangan terorisme yang menyebabkan masuknya pasien trauma, sistem triase juga harus mampu mengalokasikan sumber daya perawatan kritis secara adil kepada pasien dengan kondisi medis yang tidak terkait dengan insiden tersebut, seperti gagal napas akibat sindrom gangguan pernapasan akut karena sepsis atau wanita dengan perdarahan pasca persalinan. Ada beberapa pertimbangan utama saat merencanakan dan memberikan triase. Pertimbangan ini termasuk keputusan penting tentang siapa yang harus dipilih untuk melakukan triase, apakah triase harus dilakukan oleh individu atau tim, apakah mereka harus mengikuti protokol atau bertindak berdasarkan intuisi klinis mereka, dan terakhir, jika menggunakan protokol, berdasarkan apa protokol tersebut. Artikel berikut membahas apa itu triase saat bencana, siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya dan kapan harus dilakukan triase. Klasifikasi triase yang paling umum didasarkan pada lokasi dan tingkat perawatan dimana triase dilakukan. Triase primer terjadi di lapangan dengan tujuan menentukan prioritas penanganan di tempat kejadian dan transportasi pasien ke rumah sakit. Tujuan dari triase sekunder bervariasi tergantung pada sifat insiden tersebut. Triase tersier terjadi di dalam rumah sakit dengan tujuan memprioritaskan pasien, dan jika diperlukan mengalokasikan sumber daya, untuk perawatan definitif (operasi atau prosedur radiologi intervensi) dan perawatan intensif (terapi penunjang kehidupan).
Point of Care Testing (POCT) when Disaster
 Rumah sakit perlu memiliki perencanaan penanggulangan bencana rumah sakit yang baik untuk meminimalisir kekacauan saat terjadi bencana. Rumah sakit juga harus siap menghadapi masalah kesehatan yang muncul pada pengungsi pasca bencana. Laboratorium klinik di rumah sakit memiliki peran penting dalam kondisi bencana. Laboratorium harus memiliki persiapan pra bencana dan pasca bencana. POCT memiliki potensi yang sangat besar sebagai alat pemeriksaan laboratorium darurat baik di rumah sakit maupun di lokasi bencana untuk menjaga keselamatan pasien. POCT didefinisikan sebagai alat tes diagnostik laboratorium yang digunakan dalam situasi bencana secara efektif. Rumah sakit harus mempersiapkan POCT untuk mengatasi keterbatasan sumber listrik, SDM, dan situasi bangunan yang tidak memungkinkan menggunakan laboratorium diagnostic analyzer. POCT tersebut cocok untuk dibawa kemana saja baik di dalam rumah sakit maupun ke lokasi bencana dengan menggunakan kendaraan. Keuntungan menggunakan POCT adalah hasil pemeriksaan cepat bermanfaat bagi dokter yang merawat pasien, sehingga dapat menganalisis perkembangan kondisi pasien. Penggunaan POCT tidak perlu menggunakan tenaga khusus yang berpendidikan ilmu laboratorium tetapi dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.
Rumah sakit perlu memiliki perencanaan penanggulangan bencana rumah sakit yang baik untuk meminimalisir kekacauan saat terjadi bencana. Rumah sakit juga harus siap menghadapi masalah kesehatan yang muncul pada pengungsi pasca bencana. Laboratorium klinik di rumah sakit memiliki peran penting dalam kondisi bencana. Laboratorium harus memiliki persiapan pra bencana dan pasca bencana. POCT memiliki potensi yang sangat besar sebagai alat pemeriksaan laboratorium darurat baik di rumah sakit maupun di lokasi bencana untuk menjaga keselamatan pasien. POCT didefinisikan sebagai alat tes diagnostik laboratorium yang digunakan dalam situasi bencana secara efektif. Rumah sakit harus mempersiapkan POCT untuk mengatasi keterbatasan sumber listrik, SDM, dan situasi bangunan yang tidak memungkinkan menggunakan laboratorium diagnostic analyzer. POCT tersebut cocok untuk dibawa kemana saja baik di dalam rumah sakit maupun ke lokasi bencana dengan menggunakan kendaraan. Keuntungan menggunakan POCT adalah hasil pemeriksaan cepat bermanfaat bagi dokter yang merawat pasien, sehingga dapat menganalisis perkembangan kondisi pasien. Penggunaan POCT tidak perlu menggunakan tenaga khusus yang berpendidikan ilmu laboratorium tetapi dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.
Public health emergency preparedness (PHEP): a framework to promote resilience
 Keadaan darurat dan bencana berdampak pada kesehatan masyarakat. Penyakit menular terus berkembang, pandemi COVID-19 yang baru saja dihadapi menyebabkan morbiditas dan mortalitas dengan penyebaran penyakit yang sangat cepat. Mendefinisikan kesiapsiagaan berdasarkan evidence based masih menjadi tantangan, karena kurangnya bukti untuk menginformasikan pengurangan risiko bencana (PRB) untuk kesehatan masyarakat.Sebelum terjadi pandemi, peningkatan pengetahuan masih berfokus penanganan penyakit menular dalam scope endemi atau kasus luar biasa. Kesenjangan pengetahuan yang ada dengan kerangka kerja PHEP seharusnya seimbang untuk mencerminkan konteks dinamis dan sosial dari kedaruratan kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan masyarakat yang kompleks. Intervensi berorientasi ketahanan untuk PHEP telah diusulkan dengan mempertimbangkan kompleksitas konteks darurat dan kompleksitas latar belakang yang harus memandu strategi dalam membingkai ulang PHEP. Makalah berikut menyajikan kerangka kerja yang diturunkan secara empiris dan diinformasikan secara teoritis untuk kesiapsiagaan darurat untuk menginformasikan praktik badan kesehatan masyarakat lokal/regional. Hasil yang ditampilkan mendeskripsikan elemen penting dari sistem kesehatan masyarakat yang tangguh dan bagaimana elemen tersebut berinteraksi sebagai sistem adaptif yang kompleks. Kerangka kerja ini mengidentifikasi 11 elemen penting dari sistem kesehatan masyarakat yang tangguh dan bagaimana elemen tersebut berinteraksi sebagai sistem adaptif yang kompleks. Kerangka kerja berkaitan dengan semua aspek manajemen darurat - meliputi kesiapan, respons dan pemulihan - dan promosi kapasitas adaptif untuk mendukung ketahanan di antara lembaga kesehatan masyarakat lokal/regional.
Keadaan darurat dan bencana berdampak pada kesehatan masyarakat. Penyakit menular terus berkembang, pandemi COVID-19 yang baru saja dihadapi menyebabkan morbiditas dan mortalitas dengan penyebaran penyakit yang sangat cepat. Mendefinisikan kesiapsiagaan berdasarkan evidence based masih menjadi tantangan, karena kurangnya bukti untuk menginformasikan pengurangan risiko bencana (PRB) untuk kesehatan masyarakat.Sebelum terjadi pandemi, peningkatan pengetahuan masih berfokus penanganan penyakit menular dalam scope endemi atau kasus luar biasa. Kesenjangan pengetahuan yang ada dengan kerangka kerja PHEP seharusnya seimbang untuk mencerminkan konteks dinamis dan sosial dari kedaruratan kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan masyarakat yang kompleks. Intervensi berorientasi ketahanan untuk PHEP telah diusulkan dengan mempertimbangkan kompleksitas konteks darurat dan kompleksitas latar belakang yang harus memandu strategi dalam membingkai ulang PHEP. Makalah berikut menyajikan kerangka kerja yang diturunkan secara empiris dan diinformasikan secara teoritis untuk kesiapsiagaan darurat untuk menginformasikan praktik badan kesehatan masyarakat lokal/regional. Hasil yang ditampilkan mendeskripsikan elemen penting dari sistem kesehatan masyarakat yang tangguh dan bagaimana elemen tersebut berinteraksi sebagai sistem adaptif yang kompleks. Kerangka kerja ini mengidentifikasi 11 elemen penting dari sistem kesehatan masyarakat yang tangguh dan bagaimana elemen tersebut berinteraksi sebagai sistem adaptif yang kompleks. Kerangka kerja berkaitan dengan semua aspek manajemen darurat - meliputi kesiapan, respons dan pemulihan - dan promosi kapasitas adaptif untuk mendukung ketahanan di antara lembaga kesehatan masyarakat lokal/regional.